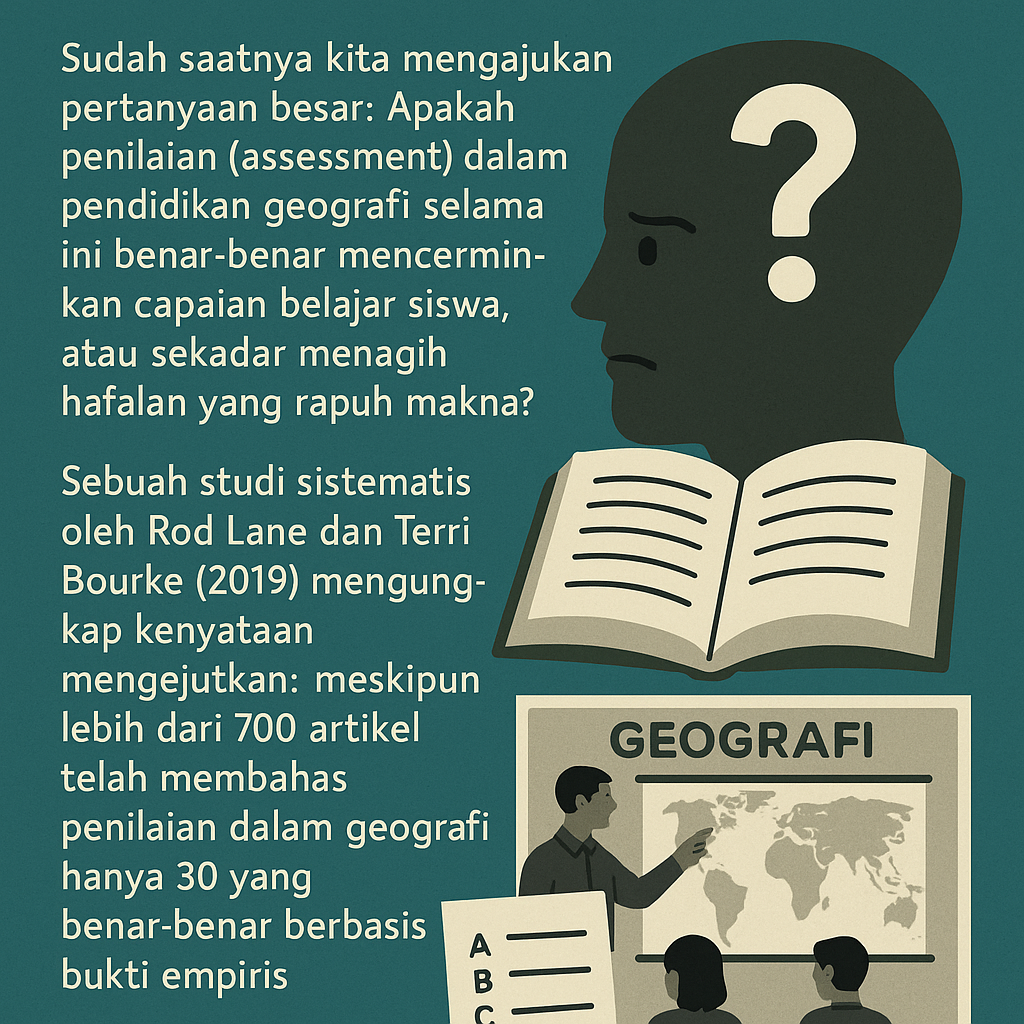Sudah saatnya kita mengajukan pertanyaan besar: Apakah penilaian (assessment) dalam pendidikan geografi selama ini benar-benar mencerminkan capaian belajar siswa, atau sekadar menagih hafalan yang rapuh makna? Sebuah studi sistematis oleh Rod Lane dan Terri Bourke (2019) mengungkap kenyataan mengejutkan: meskipun lebih dari 700 artikel telah membahas penilaian dalam geografi, hanya 30 yang benar-benar berbasis bukti empiris.
Temuan ini membuka mata kita akan krisis senyap dalam dunia pendidikan geografi. Di balik semarak jargon “pembelajaran bermakna” dan “kurikulum berbasis kompetensi”, praktik penilaian kita masih berkutat pada hal yang sama: soal pilihan ganda, hafalan konten, dan ujian akhir yang hanya mengukur sepotong kecil dari keseluruhan pemahaman geografis siswa.
Penilaian: Antara Harapan dan Kenyataan
Studi ini menyisir literatur antara tahun 2000 hingga 2016 dan menemukan delapan tema besar dalam riset penilaian geografi, mulai dari asesmen formatif, penalaran spasial, standar capaian, hingga evaluasi praktik nasional. Dari seluruh temuan tersebut, ada satu benang merah yang mengemuka: penilaian dalam geografi belum mampu mengejar kompleksitas ilmu yang diajarkannya.
Geografi bukan sekadar pengetahuan tempat, tetapi juga kemampuan untuk berpikir spasial, memahami keterkaitan antarwilayah, dan menilai dampak manusia terhadap lingkungan. Sayangnya, banyak instrumen asesmen yang masih berkutat di level rendah taksonomi kognitif: mengenali, menghafal, menjawab ulang. Padahal, kecakapan geografis justru terletak pada menganalisis, menilai, dan mencipta solusi.
AfL: Harapan dari Barat
Salah satu tema yang menjadi perhatian adalah Assessment for Learning (AfL) atau penilaian formatif. Di Inggris dan Selandia Baru, pendekatan ini terbukti mampu meningkatkan motivasi dan otonomi belajar siswa. Ketika siswa memahami kriteria keberhasilan dan diberi umpan balik yang konstruktif, mereka belajar untuk belajar.
Namun, penilaian formatif membutuhkan lebih dari sekadar rubrik. Ia menuntut perubahan budaya di ruang kelas: dari guru sebagai hakim menjadi guru sebagai fasilitator belajar. Dari siswa yang pasif menjadi siswa yang aktif mengevaluasi dirinya sendiri. Sebuah transformasi yang belum sepenuhnya terjadi di banyak sekolah, terutama di Indonesia.
Peta Spasial dan Ketimpangan
Menariknya, studi ini juga menyoroti aspek penalaran spasial. Alat ukur seperti Spatial Thinking Ability Test (STAT) mulai dikembangkan di Amerika Serikat dan diuji coba di Rwanda. Hasilnya? Siswa laki-laki dan dari perkotaan cenderung lebih unggul dibanding perempuan dan siswa desa. Ini menyingkap persoalan mendasar: akses terhadap pembelajaran berbasis geoteknologi masih timpang.
Bagaimana dengan Indonesia? Kita masih tertinggal jauh. Padahal, keterampilan membaca peta, memanfaatkan data spasial, dan memahami dinamika wilayah sangat krusial dalam menghadapi tantangan abad ke-21, termasuk perubahan iklim dan ketahanan pangan.
Kritik terhadap Praktik Penilaian Nasional
Di berbagai negara, termasuk India dan Belanda, ditemukan ketimpangan antara tujuan kurikulum dan praktik penilaian di lapangan. Soal-soal ujian masih didominasi oleh hafalan fakta, bukan kemampuan berpikir kritis atau keterampilan geografi terapan. Siswa tidak diminta menafsirkan peta, merancang solusi spasial, atau membandingkan gejala geografis secara analitis.
Indonesia pun tak kebal dari kritik ini. Cobalah tengok kisi-kisi asesmen nasional atau dulu soal UN Geografi. Sebagian besar masih menguji definisi, bukan penguasaan keterampilan spasial. Di sinilah perlunya reformasi penilaian berbasis kompetensi geografis yang sesungguhnya.
Menuju Konsensus Global
Salah satu ambisi besar yang digagas studi ini adalah pengembangan asesmen internasional untuk literasi geografis, semacam TIMSS atau PISA khusus geografi. Namun, tantangannya besar: negara-negara belum satu suara soal apa yang seharusnya diukur. Haruskah fokus pada konten, keterampilan, atau nilai-nilai kewargaan global?
Tetapi, bukankah justru dari diskusi inilah kita bisa mulai menyusun kerangka literasi geografis global? Kita butuh dialog lintas bangsa, kolaborasi peneliti, dan tentu saja komitmen kebijakan untuk menghadirkan penilaian yang adil, kontekstual, dan bermakna.
Menggugat Status Quo
Apa yang bisa kita pelajari dari kajian ini?
Pertama, kita harus jujur bahwa banyak asesmen geografi saat ini tidak mencerminkan kompleksitas dan nilai sejati disiplin ini. Kedua, kita perlu mengembangkan alat ukur yang sahih dan reliabel untuk menilai keterampilan geografis, termasuk berpikir spasial dan kemampuan argumentatif. Ketiga, kita perlu membangun ekosistem pembelajaran dan penilaian yang terintegrasi, tidak terkotak-kotak antara tujuan kurikulum, strategi pembelajaran, dan cara menguji.
Penilaian bukan sekadar pengukuran. Ia adalah cermin dari keyakinan kita terhadap apa yang penting dalam belajar. Maka, ketika penilaian masih terjebak dalam hafalan, sesungguhnya kita telah mengkerdilkan cita-cita pendidikan geografi sebagai pembentuk warga dunia yang sadar ruang, sadar lingkungan, dan sadar tanggung jawab sosialnya.
Sudah saatnya kita berubah. Dari penilaian yang mengejar angka menjadi penilaian yang menumbuhkan makna.
Referensi:
Lane, R., & Bourke, T. (2017). Assessment in geography education: a systematic review. International Research in Geographical and Environmental Education, 28(1), 22–36. https://doi.org/10.1080/10382046.2017.1385348
Transformasi pendidikan dimulai dari kita. Sahabatnya siswa dalam belajar.